Bab 8

Ayo Bangkit
“Bangunlah!
Menyesal dan bersedih tidak akan mampu mengubah hidupmu. Kau butuh gerak dan
usaha, bukan tangis dan air mata, Kekasih.
Suatu malam Ketika Pajangan diguyur hujan, aku ke SMK
untuk diskusi. Aku dan anak-anak magang telah bersepakat kalau setiap malam
kita kumpul untuk mendiskusikan terjemahan. Aku bilang, untuk menetralisir
kesalahan nerjemah, juga agar tidak terlalu nglantur dan jauh-jauh dari yang
dimaksud mushannif[1].
Aku mengirim pesan pada Anwar, mengajak ke SMK Bersama. Akhir kata, aku dan dia
berangkat ke SMK menaiki sepeda motor.
Sampai sana kita diskusi.
Kesepakatannya, setiap malam, setiap orang harus menerjemahkan lima halaman
kitab asli. Kami duduk melingkar. Ingatkah, Kau, Dik, kerudungmu yang cokelat
maroon dibias cahaya lampu terang itu menyala, menyilau kamera? Ingatkah, Kau,
Dik, siapa yang paling eksis di antara kita berlima selaian kau, yang petakilan
Ketika selfie? Apapun yang kuingat dari segalanya pada masa itu, bagiku bukan
sekedar kenangan, lebih jauh dari itu, sebuah pelajaran yang bernama “Bahagia”.
Ya, kau bisa bahagia kapan dan di mana saja.
Aku buka diskusi itu dengan bacaan “bismillah.”
Kamipun diskusi. Malam itu aku menyuruh Anwar sebagai orang pertama yang
membacakan dan mempresentasikan terjemahannya, karena kemarin, orang yang
pertama mempresentasikan karyanya adalah aku sendiri. Kenapa aku menyuruh
Anwar? Karena harapku, dia bisa dibuat contoh bagimu, Dik, juga bagi Lailana
dan Kamila. Anwar membacakan hasil terjemahannya pelan-pelan. Khidmat dan
khusyu’ benar.
Semua aku amati raut muka. Namun, kudapati Kamila
sedang menunduk lesu. Sorot matanya menghadap ke bawah.
Kutanyai ia: “Kenapa, Mbak?”
“Endak, Mas, ndapapa,” jawabnya dengan kepala
menunduk. Semuanya ikut memandangnya. Tak lama, ia masuk ke dalam kamar, entah
untuk apa. Kasihan aku dibuatnya.
“Kenapa, Kang?” tanyaku pada Anwar.
“Gatau juga, Kang,” jawabnya.
“Yasudah, kita sudahi dulu diskusi ini. Besok saja
dilanjut,” usulku.
Semuanya bubar, lalu keluar ruangan. Masakan sudah
tersedia di atas meja depan sana. Aku ikut keluar. Di luar, aku bertanya padamu
perihal Kamila, karena ia sendiri yang tidak sibuk dengan handphonenya.
“Mbak Kamila kenapa, Dik?”
“Ndatau, Mas. Tanyai saja,” jawabmu.
 |
| Buku Handphone Rahimahullah |
“Hei, kau kenapa, Mbak?”
“Tak mengapa, Mas Aqib, tak masalah.”
“Tidak. Ayo, bicaralah!”
“Malu aku, Mas Aqib,” jawabnya sambil tersedu-sedu.
Tangisnya sungguh menyanyat perasaan. Aku yakin dia sedang dilanda masalah
besar, batinku. Kamila tetap diam saja tak mau bicara.
“Ceritalah, Mbak, tak mengapa. Kenapa kau?”
“Jangan di sini,” pintamu sambil tersedan lagi “..Mas.
“Di mana?”
“Di sana aja.” Kau menunjuk arah kantin SMK.
“Ayo.”
“Eh, tapi jangan, Mas, nanti kedengeran mereka.”
“Di sana aja, di belakang SMK, gimana?”
Kau masih menangis tersedu-sedu, lalu memaksa mengatakan dalam sedu itu: “Iya, Mas, di sana aja.”
Aku mengajaknya ke belakang SMK lewat pintu belakang.
Tak ada kursi atau alas untuk dibuat duduk, aku ambilkan keramik bekas yang
tercecer di sekitar, lalu kutaruh di dekatnya. “Duduklah,” kataku padanya. Ia
masih tersedu-sedu.
Ia duduk di atas keramik itu, dekat gundukan pasir
yang digunakan untuk membangun mushola di belakang SMK, guna peserta didik. Ia
duduk sambil menyeka air matanya. Sebentar sekali setelah duduk, ia berdiri.
“Mau kemana, Mbak?” tanyaku.
“Sebentar, Mas, ambil tissue.”
Tak mengindahkan kataku ia masuk ke dalam ruangan, tak
lama ia Kembali duduk. Masih menangis. Aku sudah duduk di atas keramik bekas
yang kucari sendiri, tak jauh darinya.
“Kenapa kau sebenarnya, Mbak?” Aku membuka pembicaraan
dengan nada yang kubuat selembut mungkin. Kata orang, Wanita akan luluh hatinya
jika diperlakukan seperti anak kecil. Aku mempraktekkan padanya. Di usiaku yang
baru seumur jagung, belum pernah aku berada di posisi seperti ini.
Ia menyeka air matanya, tersedu-sedu, dan memaksa
bicara: "Malu aku, Mas.”
“Kenapa?”
“Hiks, hiks.”
“Bicaralah, Mbak! Aku tak akan bilang pada
siapa-siapa.”
“Sebenarnya aku tidak bisa Bahasa Arab sama sekali,”
katamu sambil tersedu-sedu. “Sebenarnya sebelum berangkat ke sini, aku sudah
bertanya pada Siska perihal bagaimana keadaaan di sini.”
“Terus?”
“Iya, Mas, sebentar.” Ia tersedu-sedu.
“Siska bilang kalau di sini enak, nyaman, damai, dan
tentram. Sebenarnya aku betah banget di sini. Tapi,” ia tersedak oleh
tangisnya, “tapi aku malu karena tidak bisa nerjemah. Kau tahu, Mas, dari
kemarin sebenarnya aku sudah ngetweet berkali-kali. Aku nerjamah itu
satu persatu kata tak cari di kamus, lalu lama-lama aku malu karena ketika
anak-anak sudah selesai nerjemah, aku dan Siska masih dapat satu paragraf. Aku
harus bagaimana, Mas?!”
Kemudian ia menunduk, mengambil tissue beberapa
lembar, lalu menyeka air matanya.
Aku ikut sedih. Hey, kawan, siapa yang tidak sedih
ketika seorang yang menjadi tanggung jawabmu menangis sampai seperti itu?
Akupun takt ahu bagaimana bisa ia mengeluh sampai sedalam ini. Tapi aku bangga
bukan main, karena Kamila dan Siska sudah menyadari eksistensi seorang memahami
ilmu-ilmu Tuhan. Aku tambah semangat ingin menemani mereka berdua belajar.
Kubiarkan ia menangis. Tak terasa aku ikut menitikkan
air mata. Tak tega melihat ia menangis. Andai aku ibunya, atau ayahnya, atau
kekasihnya, pastilah aku usap air matanya yang berharga itu; air mata yang
jatuh karena kecemburuan ilmu. Ya Tuhan, bahagiakan ia dengan ilmu, sebagaimana
sedihnya ia ketika cemburu pada ilmu.
Aku mengambil tissue tiga lembar, lalu menyeka air
mataku.
“Sebenarnya sudah dari kemarin aku ingin bilang pada
Mas Aqib, tapi aku takut Mas Aqib marah. Aku ta ingin ditertawakan di depan
umum karena tidak bisa bahasa Arab. Apalagi aku jurusan sastra Arab.’
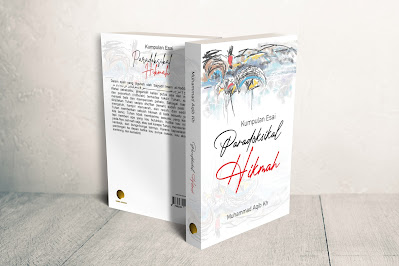 |
| Info Terkini: Buku Paradoksikal Hikmah segera ready stock. |
“Bangunlah! Menyesal dan bersedih tidak akan mampu
mengubah hidupmu. Kau butuh gerak dan usaha, bukan tangis dan air mata. Yaudah,
besok kamu sama Siska belajar nerjemah sama saya, Ya! Usulku. “Usah nangis. Aku
tak manggil Siska dulu.”
Aku bangkit dari duduk, masuk ke dalam ruangan, dan
memanggilmu.
“Dik!”
“Iya, Mas Aqib! Ada apa?”
“Ke sini,” kataku sambil melambaikan tangan, memberi
isyarat agar kau mendekat.
Kau lalu mendekat.
“Ayo ikut aku!” Aku berjalan ke belakang. Kau
mengikuti.
Sesampai di dekat Kamila, kau duduk tepat di dekatnya.
“Kenapa, Mbak?”
“Ndapapa, Sis.”
“Besok belajar bareng, waktunya siang dan malam.”
“Iya, Mas,” jawabmu.
Kamila sudah tidak menangis. Hanya menyisakan seduan.
Kau masih diam menunduk. Sedang aku menatap kolong langit yang hitam, ada
bintang gemintang bertaburan di sana. Tapi bulan sedang tidak menampakkan
wujudnya. Entah, mungkin mataku yang tidak buram karena telah menatapmu dan
mendapati wajahmu lebih bersinar dan berpendar melebihi bulan, dan ketika aku
menatap bulan, mataku buram.
Lalu ke bawah, kusapukan pandangan ke sekitar. Gelap.
Tak ada lampu yang menerangi halaman belakang SMK. Suasana saat itu sepi, tapi
suara derik jangkrik, suara kodok bangkong “kang-kong kang-kong”
benar-benar terdengar nyaring.
Lebih dari itu, Dik, suara gemuruh hatiku dan gelegar suaranya jelas-jelas terasa bunyinya di dada. Kau tahu sebabnya? Jelas! Karena kau berada di dekatku malam itu, Kekasih.
NB: Bagi kalian yang ingin mengirimkan karya, silakan membuka kolom Kirim Karya di bagian website paling bawah. Kami tunggu karyamu untuk tayang di Sabda Diksi. Semangat.
Post a Comment